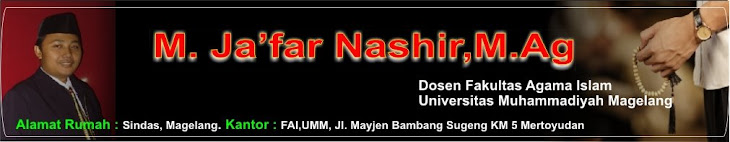Oleh : M. Ja’far Nashir
A. PENDAHULUAN
Perkembangan kebudayaan sekarang ini ............
Persoalan nilai pluralisme dan multikulturalisme merupakan tantangan utama yang dihadapi oleh agama-agama di dunia sekarang ini, mengingat setiap agama sesungguhnya muncul dari lingkungan keagamaan dan kebudayaan yang plural. Pada saat yang sama, para pemeluk agama-agama telah membentuk wawasan keagamaan mereka yang eksklusif dan bertentangan dengan semangat pluralisme dan multikulturalisme. Berbagai gerakan sering muncul dan sering menjadi sebab timbulnya wawasan dan perkembangan keagamaan baru. Dalam sejarah agama disebutkan bahwa pembaharu Budha muncul di tengah-tengah pandangan plural dari kaum Brahmais, Jaina, matrealistis, dan agnostis. Muhammad juga muncul di tengah-tengah masyarakat Mekah yang beragama terdiri dari komunitas Yahudi, Kristiani, Zoroaster, dan lainnya. Ibrahim dan Musa muncul dari lingkungan masyarakat yang menyembah berbagai macam dewa lokal.
Menyikapi bahwa Islam muncul di tengah-tengah multikulturalisme agama dan kebudayaan tersebut di atas, maka berbagai celah telah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad saw sampai dengan sekarang ini. Munculnya piagam Madina misalnya, merupakan alat yang menjembatani betapa pluralnya masyarakat pada saat itu. Ini adalah salah satu bentuk sikap Islam terhadap munculnya multikulturalisme di tengah-tengah peradaban masyarakat.
B. DEFINISI KUTUR (BUDAYA), PLURALISME, DAN MULTI-KULTURALISME
Berbicara tentang multikulturalisme tentunya tidak akan terlepas dari kultural dan pluralisme. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menjumpai kata kultur (budaya), pluralisme, dan bahkan multikultural. Dalam makalah ini sebelum kita membahas tentang apa yang dimaksud dengan multikulturalisme, sekilas terlebih dahulu akan dijabarkan tentang apa yang dimaksud dengan kultur dan pluralisme.
a) Pengertian Kultur
Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia untuk memenuhi kehidupannya dengan cara belajar, yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat. Untuk lebih jelasnya, dapat dirinci sebagai berikut : [1]
1. Bahwa kebudayaan adalah segala sesuatu yang dilakukan dan dihasilkan manusia. Karena itu meliputi :
a. Kebudayaan material (bersifat jasmaniah)
b. Kebuayaan non material
2. Bahwa kebudayaan itu tidak diwariskan secara generatif (biologis), melainkan hanya mungkin diperoleh dengan cara belajar.
3. Bahwa kebudayaan itu diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Yanpa masyarakat akan sukarlah bagi manusia untuk membentuk kebudayaan. Sebaliknya tanpa kebudayaan tidak mungkin manusia baik secara individual maupun masyarakat, dapat mempertahankan kehidupannya.
4. Jadi kebudayaan itu adalah kebudayaan manusia. Dan hampir semua tindakan manusia adalah kebudayaan, karena yang tidak perlu dibiaskan dengan cara belajar, misalnya tindakan atas dasar naluri (instink), gerak refleks. Sehubungan dengan itu kita perlu mengetahui perbedaan tingkah laku manusia dengan makhluk lainnya, khususnya hewan.
Sedangkan menurut E.B. Taylor (Bapak Antropologi Budaya) mendefinikan Budaya sebagai : ”Keseluruhan Kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan atau kebiasaan-kebiasaan lain yang diperoleh anggota-anggota suatu masyarakat”[2]
Kebudayaan pada hakekatnya tidak terlepas dari komunikasi, dalam konssep ini maka kebudayaan (budaya) adalah suatu konsep yang membangkitkan minat. Secara for,al budaya didefinisikan sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hirarki, agama, waktu, peranan, hubungan ruang, konsep alam semesta, objek-objek materi dan milik yang diperoleh sekelompok besar orangdari generasi ke generasi melalui usaha individu dan kelompok.
Budaya menampakkan diri dalam pola-pola bahasa dan dalam bentuk-bentuk kegiatan dan perilaku yang berfungsi sebagai model-model bagi tindakan-tindakan penyesuaian diri dan gaya komunikasi yang memungkinkan orang-orang tinggal dalam suatu masyarakat di suatu lingkungan geografis tertentu pada suatu tingkat perkembangan teknis tertentu dan pada suatu saat tertentu.
Budaya juga berkenaan dengan sifat-sifat dari objek-objek materi yang memainkan peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Objek-objek seperti rumah, alat dan mesin yang digunakan dalam industri dan pertanian, jenis-jenis transportasi, dan alat-alat perang, menyediakan suatu landasan utama bagi kehidupan sosial.
Budaya berkesinambungan dan hadir dimana-mana; budaya meliputi semua peneguhan perilaku yang diterima selama suatu periode kehidupan. Budaya juga berkenaan dengan bentuk dan struktur fisik serta lingkungan sosial yang mempengaruhi hidup kita. Sebagian besar pengaruh budaya terhadap kehidupan kita tidak kita sadari. Mungkin suatu cara untuk memahami pengaruh budaya adalah dengan membandingkannya dengan komputer elektronik; kita memrogram komputer agar melakukan sesuatu, budaya kita pun memrogram kita agar melakukan sesuatu dan menjadikan kita apa adanya. Budaya kita secara pasti mempengaruhi kita sejak dalam kandungan hingga mati – dan bahkan setelah mati pun kita dikuburkan dengan cara-cara yang sesuai dengan budaya kita.[3]
Oleh karena budaya memberi identitas kepada sekelompok orang bagaimana kita dapat mengidentifikasi aspek-aspek budaya yang menjadikan sekelompok orang sangat berbeda? Salah satu caranya adalah dengan menelaah kelompok dan aspek-aspeknya, antara lain :[4] Komunikasi dan Bahasa, Pakaian dan Penampilan, Makanan dan Kebiasaan Makan, Waktu dan Kesadaran Akan Waktu, Penghargaan dan Pengakuan, Hubungan-hubungan, Nilai dan Norma, Rasa Diri dan Ruang, Proses Mental dan Belajar, dan Kepercayaan dan Sikap.
b) Pengertian Pluralisme
Pengertian tentang pluralisme dapat dilihat dari definisi berbagai tokoh sebagaimana berikut ini. Josh McDowell menjelaskan mengenai definisi pluralisme ada dua macam; Pertama, pluralisme tradisional (Social Pluralism) yang kini disebut "negative tolerance". Pluralisme ini didefinisikan sebagai "respecting others beliefs and practices without sharing them" (menghormati keimanan dan praktik ibadah pihak lain tanpa ikut serta (sharing) bersama mereka). Kedua, pluralisme baru (Religious Pluralism) disebut dengan "positive tolerance" yang menyatakan bahwa "every single individual's beliefs, values, lifestyle, and truth claims are equal" (setiap keimanan, nilai, gaya hidup dan klaim kebenaran dari setiap individu, adalah sama (equal).[5]
Menurut The Oxford English Directory, pluralisme berarti “sebuah watak untuk menjadi plural”, dan dalam ilmu politik didefinisikan sebagai :
1) Sebuah teori yang menentang kekuasaan monolitik negara dan bahkan menganjurkan untuk meningkatkan pelimpahan dan otonomi organisasi-organisasi utama yang mewakili keterlibatan seseorang dalam masyarakat. Juga, percaya bahwa kekuasaan harus dibagi di antara partai-partai politik yang ada.
2) Keberadaan toleransi keragaman kelompok-kelompok etnis dan budaya dalam suatu masyarakat atau negara, keragaman kepercayaan atau sikap yang ada pada sebuah badan atau institusi dan sebagainya.[6]
Sedangkan dalam Islam yang dimaksud pluralisme adalah paham kemajemukan yang melihatnya sebagai suatu kenyataan yang bersifat positif dan sebagai keharusan bagi keselamatan umat manusia.[7]
c) Pengertian Multi-Kulturalisme
Dalam masyarakat yang majemuk (yang terdiri dari suku, ras, agama, bahasa, dan budaya yang berbeda), kita sering menggunakan berbagai istilah yaitu : pluralitas (plurality), keragaman (diversity), dan multikultural (multicultural). Ketiga ekspresi itu sesungguhnya tidak merepresentasikan hal yang sama, walaupun semuanya mengacu kepada adanya ’ketidaktunggalan’.
Dibandingkan konsep Pluralitas dan Keragaman, Multikulturalisme sebenarnya relatif baru. Menurut Bhikhu Parekh[8], baru sekitar 1970-an gerakan multikultural muncul pertama kali di Kanada dan Australia, kemudian di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan lainnya. Secara konseptual terdapat perbedaan signifikan antara pluralitas, keragaman, dan multikultural. Inti dari multikulturalisme adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa mempedulikan perbedaan budaya, etnik, jender, bahasa, ataupun agama.
Apabila pluralitas sekadar merepresentasikan adanya kemajemukan (yang lebih dari satu), multikulturalisme memberikan penegasan bahwa dengan segala perbedaannya itu mereka adalah sama di dalam ruang publik. Multikulturalisme menjadi semacam respons kebijakan baru terhadap keragaman. Dengan kata lain, adanya komunitas-komunitas yang berbeda saja tidak cukup; sebab yang terpenting adalah bahwa komunitas-komunitas itu diperlakukan sama oleh negara.
Akar kata dari multikulturalisme adalah kebudayaan. Pengertian kebudayaan diantara para ahli harus dipersamakan atau setidak-tidaknya tidak dipertentangkan antara satu konsep yang dipunyai oleh seorang ahli dengan konsep yang dipunyai oleh ahli atau ahli-ahli lainnya. Karena multikulturalsime itu adalah sebuah ideologi dan sebuah alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiannya, maka konsep kebudayaan harus dilihat dalam perspektif fungsinya bagi kehidupan manusia. Saya melihat kebudayaan dalam perspektif tersebut dan karena itu melihat kebudayaan sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Yang juga harus kita perhatikan bersama untuk kesamaan pendapat dan pemahaman adalah bagaimana kebudayaan itu operasional melalui pranata-pranata sosial.
Sebagai sebuah ide atau ideologi multikulturalisme terserap dalam berbagai interaksi yang ada dalam berbagai struktur kegiatan kehidupan manusia yang tercakup dalam kehidupan sosial, kehidupan ekonomi dan bisnis, dan kehidupan politik, dan berbagai kegiatan lainnya di dalam masyarakat yang bersangkutan Kajian-kajian mengenai corak kegiatan, yaitu hubungan antar-manusia dalam berbagai manajemen pengelolaan sumber-sumber daya akan merupakan sumbangan yang penting dalam upaya mengembangkan dan memantapkan multikulturalisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi Indonesia.
Menurut Rogers dan Steinfatt Multikulturalisme merupakan pengakuan bahwa beberapa kultur yang berbeda dapat eksis dalam lingkungan yang sama dan menguntungkan satu sama lain. Atau pengakuan dan promosi terhadap pluralisme kultural.[9] Sedang Suryadinata menyebutkan bahwa multikulturalisme menghargai dan berusaha melindungi keragaman kultural.[10]
d) Perbedaan Kulturalisme dengan Multi-Kulturalisme
Dari gambaran tersebut di atas, setidaknya dapat dilihat bagaimana sebenarnya perbedaan kultutalisme dengan multikulturalisme. Dr. Turnomo Rahardjo misalnya membedakan keduanya sebagai berikut : [11]
(1) Kulturalisme
1. Bertujuan mengembangkan interdependensi pada aspek-aspek pragmatis dan instrumental dalam kontak antarbudaya;
2. Memberikan penekanan pada pemeliharaan identitas kultural;
3. Mengkombinasikan pendekatan etic (memperoleh data) dan pendekatan emic (mendapatkan data) dalam pertukaran antarbudaya.
(2) Multikulturalisme
1. Bertujuan mempertahankan dan mentransmisikan budaya yang tidak dapat diubah oleh kekuatan-kekuatan relasional maupun eksternal;
2. Berusaha memelihara identitas kultural dengan segala konsekuensinya;
3. Merupakan proses emic (mendapatkan data) karena mensyaratkan pemeliharaan terhadap keberadaan setiap budaya.
C. RESPON ISLAM TERHADAP MULTI-KULTURALISME
Sampai batas tertentu, respons agama terhadap kecenderungan multikulturalisme memang masih ambigu. Hal itu disebabkan, agama kerap dipahami sebagai wilayah sakral, metafisik, abadi, samawi, dan mutlak. Bahkan, pada saat agama terlibat dengan urusan ’duniawi’ sekalipun, hal ini tetap demi penunaian kewajiban untuk kepentingan ’samawi.’ Berbagai agama, tentu saja, berbeda-beda dalam perkara cara dan berbagai aspek, namun agama-agama tersebut hampir seluruhnya memiliki sifat-sifat demikian itu.
Karena sakral dan mutlak, maka sulit bagi agama-agama tersebut untuk mentoleransi atau hidup berdampingan dengan tradisi kultural yang dianggap bersifat duniawi dan relativistik. Oleh karena itu, persentuhan agama dan budaya lebih banyak memunculkan persoalan daripada manfaat. Apalagi, misalnya dalam konteks Islam, kemudian dikembangkan konsep bid’ah yang sama sekali tidak memberikan ruang akomodasi bagi penyerapan budaya non-agama.
Dapatkah Islam mengembangkan multikulturalisme, sementara pada saat yang sama kurang mengembangkan apresiasi terhadap budaya, termasuk yang berperspektif lokal? Rasanya sulit menjawabnya secara afirmatif, jika gagasan multikulturalisme itu masih dianggap asing dalam mind-set Islam.
Sebenarnya, cita-cita agung multikulturalisme tidak bertentangan dengan agama; namun demikian basis teoretisnya tetap problematik. Nilai-nilai multikulturalisme dianggap ekstra-religius yang ditolak oleh para teolog Muslim, sehingga sulit untuk mengeksplorasi tema tersebut. Memang belakangan telah muncul prakarsa yang dilakukan sejumlah pemikir Arab, seperti Mohammed Abed al-Jabiri, Hassan Hanafi, Nasr Hamid Abu-Zaid, dan lain-lain, untuk merekonsiliasi antara tradisi dan agama. Namun, gagasan-gagasan mereka mendapat tanggapan keras dari ulama-ulama konservatif.
Dalam upaya membangun hubungan sinergi antara multikulturalisme dan agama, menurut Mun’im A Sirry minimal diperlukan dua hal yaitu :[12]
Pertama, penafsiran ulang atas doktrin-doktrin keagamaan ortodoks yang sementara ini dijadikan dalih untuk bersikap eksklusif dan opresif. Penafsiran ulang itu harus dilakukan sedemikian rupa sehingga agama bukan saja bersikap reseptif terhadap kearifan tradisi lokal, melainkan juga memandu di garda depan untuk mengantarkan demokrasi built-in dalam masyarakat-masyarakat beragama.
Kedua, mendialogkan agama dengan gagasan-gagasan modern. Saat ini, umat beragama memasuki suatu fase sejarah baru di mana mereka harus mampu beradaptasi dengan peradaban-peradaban besar yang tidak didasarkan pada agama, seperti kultur Barat modern. Kita tak mungkin menghindar dari ide-ide dan teori-teori sekuler. Itu berarti, menyentuh istilah-istilah dengan gagasan non-religius itu merupakan tugas paling menantang yang dihadapi kaum Muslim pada zaman modern ini.
Dr Abdolkarim Soroush,[13] intelektual Muslim asal Iran, menegaskan bahwa umat beragama dihadapkan pada dua persoalan: local problems (problem-problem lokal) dan universal problems (problem-problem universal) yakni problem kemanusiaan secara keseluruhan. Menurut dia, saat ini, problem-problem seperti perdamaian, hak-hak asasi manusia, hak-hak perempuan, telah menjadi problem global, dan harus diselesaikan pada level itu.
1. Pandangan Islam Tentang Sosio-kultural (budaya)
Agama, termasuk Islam mengandung simbol-simbol sistem sosio-kultural yang memberikan suatu konsepsi tentang realitas dan rancangan untuk mewujudkannya. Tetapi, simbol-simbol yang menyangkut realitas tidak selalu harus sama dengan realitas yang terwujud secara riil dalam kehidupan masyarakat. Dalam pengertian ini, agama dipahami sebagai suatu “sistem budaya” (cultural system).[14]
Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, jika Islam (Alqur’an) – yang diyakini kaum Muslimin sebagai kebenaran final yang tidak dapat diubah dan berlaku untuk segala waktu dan tempat – merupakan konsepsi tentang relitas, apakah Islam merupakan pendukung atau sebaliknya hambatan terhadap perkembangan budaya? Dalam bentuk yang lebih populer, apakah Islam menjadi penghalang bagi perubahan sosial yang menuju ke arah kesejahteraan kemanusiaan?
Menjawab pertanyaan tersebut tentunya kita akan melihat kembali kebelakang, bahwa sepanjang sejarah sejak masa-masa awal telah tercipta semacam ketegangan antara doktrin teologis Islam dengan relitas dan perkembangan sosial. Tetapi dalam aplikasi praktis, Islam “terpaksa” mengakomodasi kenyataan sosial budaya. Tatkala doktrin pokok Al-Qur’an tentang fiqh, misalnya dirumuskan secara terinci, ketika itu pulalah para ahli fiqh – terpaksa mempertimbangkan faktor sosial budaya. Karena itulah antara lain tercipta perbedaan-perbedaan – betapapun kecilnya, misalnya diantara imam-imam madzhab. Imam Syafi’i, misalnya mengembangkan apa yang disebut “qawl al-qadim” ketika di Irak dan “qawl al-jadid” ketika ia pindah ke Mesir.
Jadi sejak awal perkembangan Islam sebagai konsepsi realitas telah menerima akomodasi sosio-kultural. Akomodasi ini semakin terlihat ketika wilayah Islam berkembang sedemikian rupa sehingga ia menjadi agama yang mendunia. Pada kasus-kasus tertentu, akomodasi itu tercipta sedemikian rupa, sehingga memunculkan “varian Islam”.[15]
2. Sikap Masyarakat Madani (Islam) Terhadap Multi-Kulturalisme
Sebagaimana kota Jakarta, kota-kota besar dunia Islam pada masa kejayaannya, terutama Baghdad dan Kordoba, merupakan masyarakat yang majemuk (plural), dimana penduduk dari pelbagai latar belakang etnik, suku, bangsa dan agama berkumpul dan hidup bersama. Tentu saja, keadaan ini menimbulkan tantangan-tantangan tersendiri yang perlu dijawab oleh masyarakat perkotaan dengan mengembangkan sifat-sifat yang cocok dengan keadaan. Sifat-sifat yang cocok dengan keadaan masyarakat kota inilah yang dimaksud dengan masyarakat madani-multikultural dan tentu saja melibatkan sikap-sikap tertentu yang menjadi tuntutan masyarakat multikultural. Sikap-sikap tersebut menurut Mulyadhi Kartanegara di golongkan menjadi empat, antara lain meliputi inklusivisme, humanisme/egalitarianisme, toleransi, dan demokrasi.[16]
a) Inklusivisme
Sikap inklusif sebenarnya telah dipraktekkan oleh para adib ketika menyusun “adab” mereka. Dalam menentukannya selain menggunakan al-Qur’an dan hadits sebagai sumber paling otoritatif, mereka juga masih menggunakan sumber-sumber dari kebudayaan lain.[17] Selain para adib (udaba’) , para ilmuwan dan filosof Muslim juga telah mengembangkan sikap inklusif yang serupa dalam karya mereka. Mereka menunjukkan sikap lapang dada dan percaya diri yang luar biasa terhadap pemikiran-pemikiran yang datang dari luar, dan tak nampak sedikitpun rasa minder dalam diri mereka. Sikap inklusif ini dapat dilihat dari tokoh-tokoh filosof Muslim dalam berfilsafat dan juga dalam mencari guru.[18]
b) Humanisme/egalitariaanisme
Yang dimaksud humanisme disini adalah cara pandang yang memperlakukan manusia karena kemanusiaannya, tidak karena sebab yang lain di luar itu, seperti ras, kasta, warna kulit, kedudukan, kekayaan dan bahkan agama. Dengan demikian termasuk di dalam humanisme ini adalah sifat egaliter, yang menilai semua manusia sama derajatnya. Sejarah kebudayaan Islam sarat dengan contoh-contoh sifat humanis ini. Nabi kita sendiri disinyalir pernah menyatakan dengan tegas, bahwa “tidak ada kelebihan seorang Arab daripada ‘ajam (non-Arab)”.
Contoh lain yang berkenaan dengan humanisme adalah : pembelaan oleh Jalal al-Din Rumi kepada muridnya yang beragama Kristen[19], dan juga dapat kita lihat dari kitab al-Akhlaq wa al-Siyar, karangan Ibn Hazm (w.1066), yang intinya pandangan Ibn Hazm terlihat jelas ketika, misalnya, ia mengritik seseorang yang terlalu bangga dengan keturunannya.
c) Toleransi
Toleransi umat Islam barangkali dapat dilihat dari beberapa contoh di bawah ini : Pada Masa awal Islam, Para penguasa Muslim dalam waktu yang relatif singkat telah menaklukkan beberapa wilayah sekitarnya seperti; Mesir, Siria, dan Persia. Ketika para penguasa Muslim menaklukkan daerah tersebut, di sana telah ada dan berkembang dengan pesat beberapa pusat ilmu pengetahuan. Dan setelah daerah tersebut dikuasai Islam, kegiatan keilmuan masih berjalan dengan baik tanpa ada campur tangan dari penguasa Muslim.
Disamping itu komunitas non-Muslim seperti Kristen, Yahudi, dan bahkan Zoroaster dapat hidup dan menjalankan ibadah mereka masing-masing dengan relatif bebas di bawah kekuasaan para penguasa Muslim. Sikap lain yang ditunjukkan adalah diperkenankannya kaum non-Muslim untuk hadir dan mengikuti kajian-kajian ilmiah yang diselenggarakan orang-orang Muslim, baik sarjananya maupun penguasanya.
d) Demokrasi
Menurut Abdolkarim Soroush dalam bukunya Reason, Freedom and Democracy in Islam, salah satu sifat yang tidak boleh ditinggalkan dalam demokrasi adalah kebebasan individu untuk mengemukakan pendapatnya, dengan kata lain harus ada kebebasan berfikir.[20] Kebabasan inilah yang telah dilaksanakan oleh masyarakat di kota-kota besar Islam, terutama pada masa kejayaan Islam.
Pada kesempatan yang lain, Samsu Rizal Panggabean[21] memberikan gambaran mengenai pandangan Islam tentang Multikulturalisme, yang mana dia menjelaskan bahwa kenekaragaman itu sendiri ada dalam tubuh Islam (masyarakat Islam), disamping kenekaragaman yang terjadi di luar Islam. Dalam tulisannya yang berjudul Islam dan Multikulturalisme, Rizal membahas multikulturalisme dalam dua arah pembicaraan, yaitu : multikulturalisme dari komunitas Muslim (Multikulturalisme Internal) dan komunitas agama-agama lain (Multikulturalisme Eksternal).
a) Multikulturalisme Internal
Multikultuiralisme Internal adalah keanekaragaman internal dikalangan umat Islam, ini menunjukkan bahwa kebudayaan Islam itu majemuk secara internal. Dalam hal ini, kebudayaan Islam serupa dengan kebudayaan-kebudayaan lainnya kecuali kebudayaan yang paling primitif. Kemajemukan internal ini mencakup antara lain : Bidang pengelompokan sosial; Bidang fiqh; Bidang teologi, Bidang tasawuf dan dimasa modern seperti politik kepartaian.
Dilihat dari sudut multikulturalisme internal ini, pluralisme identitas kultural keagamaan dalam masyarakat Muslim bukan hanya merupakan fakta yang sulit dipungkiri. Lebih dari itu, multikulturalisme juga menjadi semangat, sikap, dan pendekatan. Dalam hal ini, setiap identitas kultural terus berinteraksi dengan dengan identitas kultural yang lain di dalam tubuh umat. Melalui interaksi itu, setiap identitas mendefinisikan identitasnya dalam kaitannya dengan identitas yang lain dan karenanya, secara sadar atau tidak, suatu identitas dipengaruhi identitas yang lain. Multikulturalisme internal ini, dengan demikian, mengisyaratkan kesediaan berdialog dan menerima kritik.
b) Multikulturalisme Eksternal
Multikultural eksternal ditandai dengan pluralitas komunal-keagamaan, merupakan fakta yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat Muslim. Dimasa lalu, imperium-imperium Islam, walaupun ada penisbatan dan pelabelan Islam pada namanya, selalu bercirikan multikultural dalam pengertian keanekaragaman komunitas keagamaan. Imperium besar seperti Usmani di Turki meupun imperium yang lebih kecil seperti Ternate dan Tedore di wilayah Timur Nusantara selalu mencakup lebih dari dua komunitas kultural-keagamaan.
Dilihat dari sudut multikulturalisme eksternal ini, pluralisme keagamaan bukan hanya merupakan fakta yang tidak dapat dihindari. Lebih dari itu, multikulturalisme juga menjadi semangat, sikap, dan pendekatan terhadap keanekaragaman budaya dan agama. Sebagai bagian dari kondisi yang majemuk, umat Islam terus berinteraksi dengan umat dari agama-agama lain. Melalui proses interaksi ini, umat Islam memperkaya dan diperkaya tradisi keagamaan lain, dan umat agama lain memperkaya dan diperkaya tradisi keagamaan Islam. Sejarah menunjukkan bahwa ufuk intelektual dan moral peradaban Islam menjadi luas dan agung dengan atau setelah membuka diri terhadap masukan dan pengaruh dari kebudayaan dan peradaban lain – bukan dengan mengurung diri di dalam ghetto kultural yang sumpek dan absolutis.
D. PENUTUP
Pada akhir tulisan ini penulis dapat menarik kesimpulan dan dengan kesimpulan tersebut setidaknya mendapatkan gambaran yang cukup jelas tentang Respon Islam terhadap Multi-Kulturalisme, sehingga diharapkan dapat lebih memperjelas apa yang telah digambarkan di atas. Dan dengan kesimpulan tersebut pula setidaknya penulis dapat memberikan beberapa saran yang nantinya semoga dapat dipertimbangkan. Adapun kesimpulan dan saran adalah sebagai berikut :
a. Kesimpulan
1). Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia untuk memenuhi kehidupannya dengan cara belajar, yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat
2). Pluralisme adalah paham kemajemukan yang melihatnya sebagai suatu kenyataan yang bersifat positif dan sebagai keharusan bagi keselamatan umat manusia
3). Multikulturalisme merupakan pengakuan bahwa beberapa kultur yang berbeda dapat eksis dalam lingkungan yang sama dan menguntungkan satu sama lain. Atau pengakuan dan promosi terhadap pluralisme kultural
4). Sejak awal perkembangan Islam sebagai konsepsi realitas telah menerima akomodasi sosio-kultural. Akomodasi ini semakin terlihat ketika wilayah Islam berkembang sedemikian rupa sehingga ia menjadi agama yang mendunia. Pada kasus-kasus tertentu, akomodasi itu tercipta sedemikian rupa, sehingga memunculkan “varian Islam”
5). Masyarakat yang majemuk (plural) -- dimana penduduk dari pelbagai latar belakang etnik, suku, bangsa dan agama berkumpul dan hidup bersama -- akan menimbulkan tantangan-tantangan tersendiri yang perlu dijawab oleh masyarakat perkotaan dengan mengembangkan sifat-sifat yang cocok dengan keadaan. Sifat-sifat yang cocok dengan keadaan masyarakat kota inilah yang dimaksud dengan masyarakat madani-multikultural dan tentu saja melibatkan sikap-sikap tertentu yang menjadi tuntutan masyarakat multikultural. Sikap-sikap tersebut antara lain meliputi inklusivisme, humanisme/egalitarianisme, toleransi, dan demokrasi.
b. Saran
Sebagai masyarakat Muslim yang senantiasa menghagai perbedaan, tentunya kita tidak serta merta menuduh bahwa yang lain itu salah, dan mengklaim bahwa hanya dirinya sendiri yang benar. Kita sebagai umat Muslim tentunya harus mengamalkan apa yang diajarkan agama Islam, dimana ajaran Islam mengajarkan kita untuk saling kenal-mengenal. Ini berarti bahwa keanekaragaman budaya merupakan suatu anugrah tersendiri dari Allah SWT kepada kita, sebagai bahan renungan, keilmuan, dan penelitian.
DAFTAR PUSTAKA
Aajid Fakhry, A History of Islamic Philosophy, cet. II, London & New York, Colombia University Press, 1983
Abdolkarim Soroush, Reason, Freedom and Democracy in Islam : Essential Writing of Abdolkarim Soroush, (ed. Dan terj. Mahmud Sadri dan Ahmad Sadri), Oxford, Oxford University Press, 2000
Amin Abdullah, Prof. Dr., Dinamika Islam Kultural; Pemetaan atas Wacana Keislaman Kontemporer. 2000.
Azyumardi Azra, Prof. Dr., MA., Konteks Berteologi di Indonesia (Pengalaman Islam), Jakarta, Paramadina, 1999.
Deddy Mulyana, Dr., MA., dan Drs, Jalaludin Rakhmat, M.Sc., (Editor), Komunikasi Antarbudaya (Panduan Berkomunikasi dengan Orang-orang Berbeda Budaya), Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, Cet. IV, 2000
Djoko Widagdo, Drs., Dkk, Ilmu Budaya Dasar, Jakarta, Bumi Aksara, 1991
Endang Turmudi dan Riza Sihbudi (Ed.), Islam dan Radikalisme di Indonesia, Jakarta, LIPI Press, 2005
Everett M. Rongers, Thomas M. Steinfatt, Intercultural Communication, Illinois, Waveland Press, Inc., 1999
Gurpreet Mahajan, Democracy, Difference and Justice, 1998
http://www.ananswer.org/mac/answeringpluralism.html, diakses 11/06/05
Joel L. Kraemer, Philosophy in the Renaissance of Islam, Leiden, E.J. Brill, 1986
Leo Suryadinata, Indonesia State Policy toward Ethnic Chinese : From Asimilation to Multiculturalism?, dalam simposium Internasional III Jurnal Antropologi Indonesia, Universitas Udayana, Bali, 2002
Masykuri Abdillah, Dr., Demokrasi di Persimpangan Makna (Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)), Yogyakarta, PT. Tiara Wacana, 1999
Mu’mun Murod Al-Barbasy. Dkk. (Ed.), Muhammadiyah – NU (Mendayung Ukhuwah di Tengah Perbedaan), Malang, UMM Press, 2004.
Mulyadhi Kartanegara, Islam dan Multikulturalisme ; Sebuah Cermin Sejarah, dalam Zakiyuddin Baidhawy dan M. Thoyibi (Ed.), Reinvensi Islam Multikultural, Surakarta, Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005
Mulyadhi Kartanegara, Islam dan Multikulturalisme ; Sebuah Cermin Sejarah, dalam Zakiyuddin Baidhawy dan M. Thoyibi (Ed.), Reinvensi Islam Multikultural,
Mun’im A Sirry, Agama, Demokrasi, dan Multikulturalisme, Artikel.
Samsu Rizal Panggabean, Islam dan Multikulturalisme (Ragam Manajemen Masyarakat Plural) dalam Zakiyuddin Baidhawy dan M. Thoyibi (Ed.), Reinvensi Islam Multikultural, Surakarta, Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005
Sukron Kamil (Peta Pemikran Politik Islam Modern dan Kontemporer), Artikel, http://www.paramadina.ac.id/html/research/314-sukron.pdf. Hlm. 73 diakses tanggal 29/11/2005
Turnomo Rahardjo, Dr., Menghargai Perbedaan Kultural (Mindfulness dalam Komunikasi Antaretnis), Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005
[1] Drs. Djoko Widagdo, Dkk, Ilmu Budaya Dasar,
[2] Dr. Deddy Mulyana, MA., dan Drs, Jalaludin Rakhmat, M.Sc., (Editor), Komunikasi Antarbudaya (Panduan Berkomunikasi dengan Orang-orang Berbeda Budaya), Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, Cet. IV, 2000, hlm. 56
[3] Ibid., hlm. 11-12
[4] Ibid., hlm. 58-63
[5] http://www.ananswer.org/mac/answeringpluralism.html, diakses 11/06/05
[6] Dalam buku karangan Dr. Masykuri Abdillah, Demokrasi di Persimpangan Makna (Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)), Yogyakarta, PT. Tiara Wacana, 1999, hlm. 146.
[7] Sukron Kamil (Peta Pemikran Politik Islam Modern dan Kontemporer), Artikel, http://www.paramadina.ac.id/html/research/314-sukron.pdf. Hlm. 73 diakses tanggal 29/11/2005
[8] Gurpreet Mahajan, Democracy, Difference and Justice, 1998
[9]
[10] Leo Suryadinata, Indonesia State Policy toward Ethnic Chinese : From Asimilation to Multiculturalism?, dalam simposium Internasional III Jurnal Antropologi Indonesia, Universitas Udayana, Bali, 2002
[11] Dr. Turnomo Rahardjo, Menghargai Perbedaan Kultural (Mindfulness dalam Komunikasi Antaretnis),
[12] Mun’im A Sirry, Agama, Demokrasi, dan Multikulturalisme, Artikel.
[13] Dr. Abdolkarim Soroush, (2000), Rason, Freedom & Democracy in Islam.
[14] Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA., Konteks Berteologi di Indonesia (Pengalaman Islam), Jakarta, Paramadina, 1999. hlm. 11
[15] Ibid., hlm. 12
[16] Mulyadhi Kartanegara, Islam dan Multikulturalisme ; Sebuah Cermin Sejarah, dalam Zakiyuddin Baidhawy dan M. Thoyibi (Ed.), Reinvensi Islam Multikultural, Surakarta, Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005, hlm. 202.
[17] Aajid Fakhry, A History of Islamic Philosophy, cet. II, London & New York, Colombia University Press, 1983, hlm. 35.
[18] Mulyadhi Kartanegara, Islam dan Multikulturalisme ; Sebuah Cermin Sejarah, dalam Zakiyuddin Baidhawy dan M. Thoyibi (Ed.), Reinvensi Islam Multikultural,hlm. 203 - 205
[19] Joel L. Kraemer, Philosophy in the Renaissance of Islam,
[20] Abdolkarim Soroush, Reason, Freedom and Democracy in Islam : Essential Writing of Abdolkarim Soroush, (ed. Dan terj. Mahmud Sadri dan Ahmad Sadri), Oxford, Oxford University Press, 2000, hlm. 89
[21] Samsu Rizal Panggabean, Islam dan Multikulturalisme (Ragam Manajemen Masyarakat Plural) dalam Zakiyuddin Baidhawy dan M. Thoyibi (Ed.), Reinvensi Islam Multikultural, Surakarta, Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005, hlm. 215-227